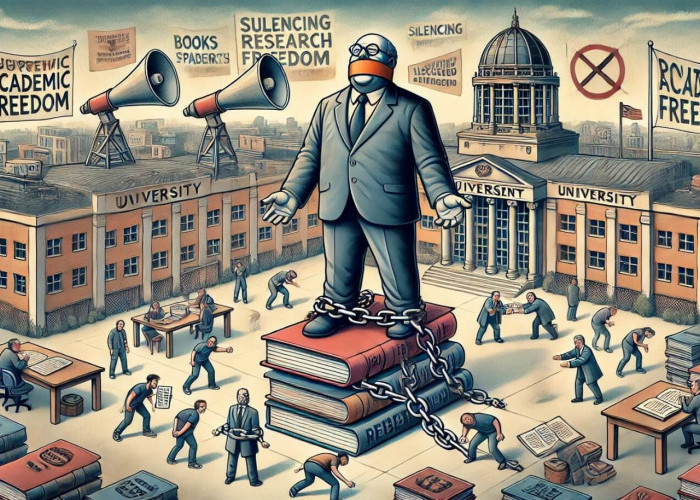Safari Harmoko

Suatu saat saya harus ”minta petunjuk” Pak Harmoko: akan mengambil alih harian Merdeka Jakarta. Yang legendaris itu.
Tanpa restu menteri penerangan hal itu akan bahaya.
Sebenarnya kata ”mengambil alih” kurang tepat. Bapak BM Diah-lah yang meminta saya mengelola koran tertua di Indonesia yang masih hidup saat itu. Beliau adalah pemilik koran itu. Beliau tokoh besar pers Indonesia. Mantan ketua umum PWI Pusat. Mantan menteri penerangan. Beliau sakit-sakitan. Harian Merdeka terancam mati.
Pak Harmoko tidak langsung memberikan restu. Tapi juga tidak langsung memberi isyarat menolak. Sebagai sesama Jawa saya harus tahu membawa diri: saya beralih ke pembicaraan lain.
Seminggu setelah lapor itu, saya dipanggil Pak Harmoko. “Bagus,” kata beliau. “Nanti yang jadi pemimpin umumnya xxxx,” kata beliau, menyebut satu nama.
Ganti saya yang tidak langsung bereaksi. Sambil tetap tersenyum saya manggut-manggut. Saya tidak mengucapkan kata apa pun. Lalu mengalihkan pembicaraan ke soal lain.
Keluar dari ruang kerja beliau saya pusing. Orang yang ditunjuk menjadi pemimpin umum harian Merdeka yang baru nanti saya kenal. Politisi. Loyalis. Bukan pengusaha. Bukan wartawan.
Maka saya harus cari akal untuk menolak nama itu. Harus dengan cara yang benar –cara Jawa. Saya kan ingin koran itu maju. Kalau nama itu yang tampil menjadi pemimpin umumnya pasti sulit berkembang. Koran itu nanti akan terasa terlalu Golkar. Saya pun memutuskan untuk sementara tidak bertemu Pak Harmoko lagi. Biar beliau lupa dulu.
Lalu datanglah ide baik. Pak Harmoko itu kan nasionalis. Beliau pernah menjadi aktivis GSNI –Gerakan Siswa Nasionalis Indonesia. BM Diah itu juga nasionalis. Soekarnois. Harian Merdeka itu sangat nasionalis. Pak Harmoko pernah berkarir di harian Merdeka. Sebagai wartawan dan karikaturis.
Akhirnya saya bertemu Pak Harmoko. Saya bilang dengan nada yang amat sangat sopan. Dengan dua tangan ngapurancang. Dengan mata menatap ke lantai.
“Pak Harmoko, semua koran sekarang ini kan sudah Golkar. Bagaimana kalau tetap ada satu koran yang nasionalis. Satu saja. Biar kesannya tetap baik. Saya janji akan menjaganya. Kami kan tahu batas,” kata saya.
Pak Harmoko diam sejenak. Lalu: ”Ya sudah, Dik Dahlan atur”.
Pak Harmoko sering menyebut diri sebagai orang pergerakan. Beliau bergerak terus. Jadi pemimpin terus. Beliau menjadi ketua PWI Jakarta. Lalu, ketika PWI Pusat pecah –ada kubu Ketua Umum BM Diah dan kubu Ketua Umum Rosihan Anwar– Pak Harmoko yang kemudian tampil sebagai pemenang. Dua tokoh pers itu saling mengklaim sebagai ketua umum yang sah. Pak Harmoko yang menjadi ketua umum tunggal berikutnya.
Beliau teguh. Termasuk menghadapi penilaian negatif pada dirinya. Misalnya ketika beliau mendirikan koran Pos Kota. Koran jenis baru di Indonesia saat itu. Kecaman datang bertubi-tubi. Setengah melecehkan. Kok bikin koran kuning seperti itu.
Tapi Pak Harmoko teguh. Di seluruh dunia koran seperti itulah yang oplahnya paling besar. Dan beliau benar. Pos Kota menjadi koran terbesar di Jakarta –secara oplah. Iklan mininya berhalaman-halaman. Menjadi kaya. Bikin percetakan modern. Bikin koran-koran lainnya lagi. Termasuk harian Surya di Surabaya –yang kemudian diambil alih grup Kompas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: