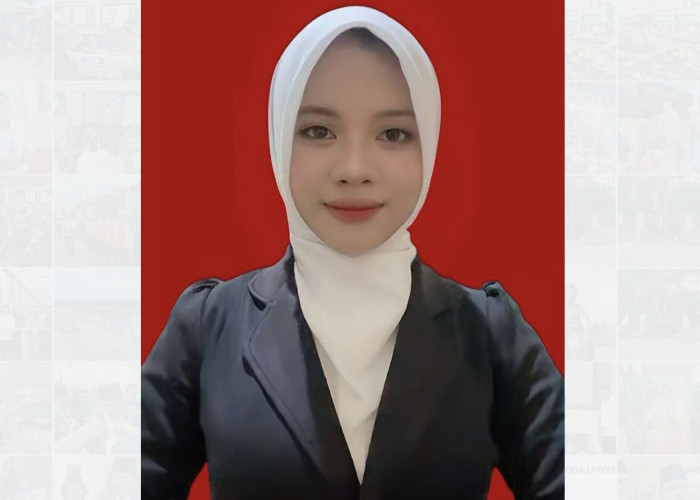Persiapan Menjadi Ibu Kota

Apa yang anda bayangkan ketika mendengar nama Jakarta? Bagaimana jika Bali? Atau Jogjakarta? ====≠============================== JIKA bayangan anda tentang kerumunan orang lalu lalang berbelanja sambil tertawa atau sedang menawar harga barang atau sedang selonjoran sambil makan di lesehan, berarti kemungkinan besar itu potret liburan akhir tahun lalu. Ada juga gedung-gedung tinggi, jalan tol dan pusat perbelanjaan lengkap. Tapi, apa yang berbeda dari ketiganya? Kota besar selalu identik dengan infrastruktur yang bagus, moderenitas dan segala hal dibuat mudah tanpa perlu bersusah payah. Selera ataupun kebutuhan masyarakatnya bisa diseragamkan. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan, hiburan, semua bisa diseragamkan atau paling tidak dibuat memiliki standar tertentu yang itu semua bisa propagandakan lewat majalah, papan reklame atau iklan yang masif di media elektronik. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua seakan sudah terprogram. Tentu saja itu semua gaya hidup kalangan atas. Bagaimana dengan kelas menengah? Kelas menengah pun memiliki standar sendiri, karna propaganda kebutuhan juga menyasar kelas ini. Ketiga daerah tadi memiliki ciri sebagai daerah yang maju/besar. Jakarta, Bali dan Jogjakarta menyuguhkan semua kebutuhan kelas atas dan menengah sembari menjadi pengharapan kelas yang di bawahnya lagi. Lalu apa yang membedakan ketiganya? Tata nilai kehidupan sosial ketiga daerah tersebut sangat berbeda, atau dengan kata lain budaya lah yang membedakan ketiga kota tersebut. Di Bali dan Jogjakarta, kehidupan modern bisa berbagi ruang dengan budaya masyarakat setempat. Jika di Jakarta dengan status Ibu Kota Negara, ruang budaya terasa terpinggirkan bersamaan dengan arus besar keluar masuk manusia, di Bali dan Jogja justru kearifan lokal membaur dan menjadi nilai tersendiri bagi para pendatang. Sederhananya, jika kita memakai perumpamaan “mewarnai atau diwarnai”, maka Bali dan Jogja lebih mampu mewarnai segala aspek kehidupan masyarakatnya tanpa terganggu atau mengganggu arus keluar masuknya manusia dari luar, sedangkan di Ibu Kota “warna-warna” nyaris saling bercampur. Ibu kota sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan menyedot banyak sekali orang dengan berbagai latar belakang dan budayanya masing-masing, namun membiarkan sebuah daerah kehilangan jati dirinya juga merupakan dosa sejarah kepada generasi berikutnya. Menjadi Ibu Kota berarti juga menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, modernitas, kepentingan dan berbagai hal lainnya yang lambat laun dapat mempengaruhi kearifan lokal. Maka Ibu Kota harusnya mampu seperti Bali dan Jogja yang nilai-nilai budayanya melekat dan hidup di masyarakat tanpa harus terpengaruh dengan arus besar keluar masuk orang. Diperlukan strategi budaya sebagai tameng sosial, di mana individu merasa terpanggil untuk mengejewantahkan nilai-nilai kearifan lokal berdampingan dengan moderenitas. Bapak Presiden sudah menetapkan Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan, maka bersiap lah menjadi “orang pusat” dengan segala kerumitan, tantangan dan peluangnya. Hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah bagaimana agar nilai-nilai budaya tidak luntur apalagi tergusur oleh infrastruktur. *penulis adalah pemerhati sosial, ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Perguruan Tinggi Kaltim Periode 2013-2017.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: